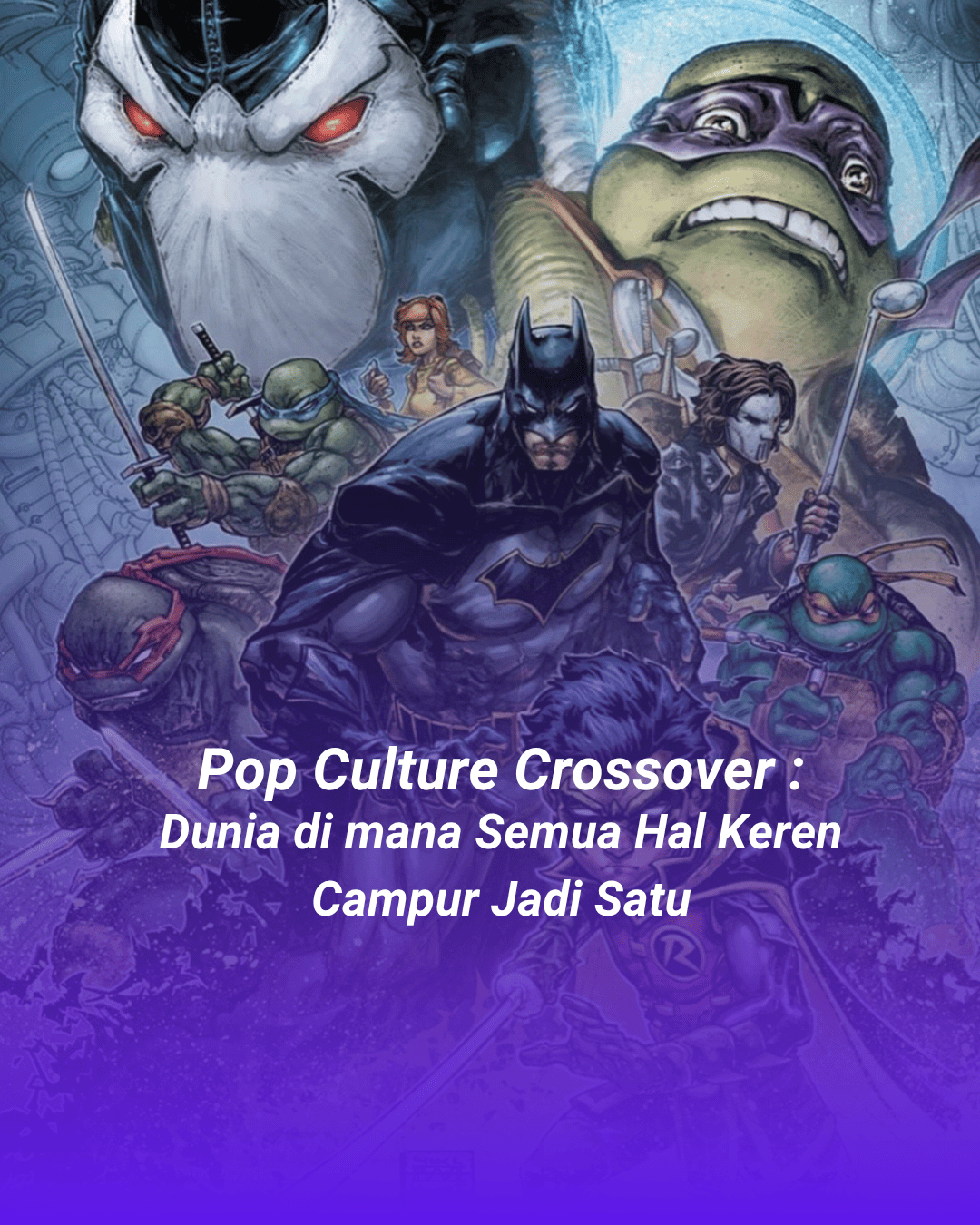
Manusia sepertinya punya kemampuan unik: menyatukan segala hal yang awalnya tidak berhubungan, lalu menjualnya dengan harga absurd. Tahun 2025 adalah puncak dari itu — era di mana film bisa menjual sepatu, game bisa melahirkan merek baju, dan seniman bisa jadi bintang TikTok karena gambar monster lucu di iPad.
Fenomena ini bukan sekadar tren, tapi ekonomi baru: ekonomi kolaborasi lintas dunia hiburan. Pop culture bukan lagi kategori, tapi ekosistem.
1. Ketika game jadi fashion show
Mari mulai dari game, pusat gravitasi generasi digital. Dulu, gamer disebut antisosial; sekarang, mereka trendsetter.
Game seperti Fortnite, Valorant, dan Genshin Impact tak lagi sekadar arena pertempuran, tapi juga panggung kolaborasi mode.
Balenciaga sempat bikin koleksi Fortnite. Louis Vuitton mendesain kostum karakter Final Fantasy. Nike merilis sepatu “League of Legends”. Bahkan di Roblox, merek mewah seperti Gucci dan Vans bikin “toko virtual” di mana anak SMP bisa nongkrong sambil pamer skin digital seharga motor bekas.
Yang menarik: industri mode dan game sama-sama paham satu hal—status sosial kini bisa digital. Kamu nggak perlu punya tas asli kalau bisa punya versi 3D-nya yang bisa dipamerkan di avatar. Dunia virtual menjadi catwalk global.
2. Film, mainan, dan strategi nostalgia
Hollywood mungkin kehabisan ide, tapi mereka masih punya mesin waktu: nostalgia.
Tahun ini saja, dunia digempur oleh film adaptasi dari mainan dan game — dari “Barbie” yang mengubah warna pink jadi alat kapitalisme terselubung, sampai “The Legend of Zelda” yang sedang disiapkan jadi film live-action.
Mainan pun membalas: setiap film besar selalu diikuti merchandise, figur, dan blind-box edisi terbatas. Film jadi alasan untuk menjual mainan, dan mainan jadi alasan untuk menonton film.
Tak heran, studio kini merancang film dengan “potensi jualan” di pikiran, bukan semata plot.
Hasbro, Mattel, dan Funko tak lagi hanya memproduksi, tapi juga mengkurasi imajinasi kolektif.
Kamu suka karakter di film? Bagus. Sekarang kamu bisa punya versi chibi-nya, glow in the dark, dan tentu saja “exclusive only at Comic-Con.”
3. Seni dan street culture masuk ke arena
Yang dulu dianggap pinggiran — grafiti, ilustrasi alternatif, desain mainan independen — sekarang adalah bagian resmi dari mesin industri.
Seniman seperti KAWS, Takashi Murakami, Hajime Sorayama, atau Brian Donnelly menjadi simbol “art-meets-commerce.” Mereka menjual patung, figur, NFT, sneakers, bahkan botol air mineral yang dianggap “limited art piece.”
Murakami berkolaborasi dengan Billie Eilish, KAWS dengan Uniqlo, Sorayama dengan Dior.
Ketika seni tinggi bertemu pop culture, hasilnya bukan lagi museum — tapi antrian panjang di depan toko retail.
Street art juga menular ke dunia digital. Gaya ilustrasi yang dulu muncul di tembok kota kini hadir di NFT, di video game, atau jadi motif hoodie.
Kamu bisa pakai hoodie bergambar karya seniman kontemporer, lalu memainkannya di game sebagai skin karakter. Batas antara seni dan konsumsi hancur, dan entah kenapa manusia suka sekali saat itu terjadi.
4. Dari merchandise ke identitas
Generasi sekarang tidak cuma mengoleksi, tapi membangun identitas melalui pop culture.
Orang tidak sekadar nonton film Marvel, tapi hidup sebagai penggemar Marvel. Tidak sekadar main Genshin, tapi jadi bagian komunitasnya.
Pop culture adalah paspor sosial — tanda bahwa kamu bagian dari “tribe” tertentu.
Brand paham ini. Maka mereka menciptakan experience, bukan produk.
Contoh: pameran kolaboratif antara Netflix x Stranger Things, konser virtual dalam game (Fortnite x Ariana Grande), atau Uniqlo x anime yang bikin antrean sampai subuh. Semua itu bukan tentang baju, tapi rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar — walau untuk itu kamu harus rela beli kaos bergambar monster seharga Rp499 ribu.
5. Efek domino digital
Internet dan media sosial mempercepat semuanya.
TikTok, Instagram, dan YouTube jadi mesin promosi lintas dunia: satu klip fanart bisa melahirkan tren fashion, satu meme dari game bisa melahirkan kolaborasi merek besar.
Kreator independen juga ikut main: banyak ilustrator dan 3D artist di Asia Tenggara mendadak viral karena gaya visual mereka yang “pop culture banget.” Dari situ mereka dapat kolaborasi brand, bahkan lisensi untuk bikin figur resmi.
Seni tak lagi butuh galeri; yang dibutuhkan hanyalah engagement rate.
Setiap like, share, dan repost adalah bentuk apresiasi — dan bentuk komodifikasi juga, tentu saja. Dunia ini absurd tapi produktif.
6. Indonesia di tengah gelombang ini
Tren ini tidak berhenti di luar negeri.
Indonesia pelan tapi pasti jadi ladang subur bagi kolaborasi pop culture.
Contoh:
- Goodbye Java, brand lokal yang memadukan desain game, musik, dan nostalgia 2000-an.
- NeverTooLavish, komunitas yang menggabungkan custom sneakers, art, dan aktivisme sosial.
- Kolaborasi IP lokal seperti Si Juki, Ghost Parade, atau Tahara dengan fashion brand dan game developer lokal.
Masih banyak ruang untuk berkembang. Pop culture adalah bisnis rasa, dan rasa itu global.
Kreator lokal yang paham storytelling dan visual identity bisa menembus pasar internasional tanpa harus jadi “versi lokal Marvel”.
7. Harga sebuah fantasi
Kelemahan dari semua ini? Ya, manusia makin sulit membedakan antara “kreativitas” dan “komoditas.”
Setiap ide keren langsung dijual, setiap karakter lucu dijadikan NFT, setiap seni diproduksi massal.
Tapi mungkin begitulah mekanisme pertahanan modern: manusia mengubah imajinasi jadi barang supaya tidak terasa sia-sia.
Sisi baiknya, industri ini mempekerjakan ribuan seniman, desainer, animator, dan pembuat konten.
Sisi gelapnya, kapitalisme belajar cara baru menjual mimpi.
Dunia pop culture sekarang seperti sirkus digital yang menghibur sekaligus menguras dompet. Tapi jujur, tanpa itu, dunia akan terasa lebih membosankan.
8. Kesimpulan: Dunia Fantasi, Dunia Nyata
Pop culture crossover bukan cuma soal kolaborasi antar-merek. Ini cerminan cara manusia modern memaknai realitas.
Ketika batas antara nyata dan virtual, seni dan komoditas, fandom dan identitas jadi kabur — yang tersisa adalah satu hal: cerita.
Semua industri — film, game, fashion, toys — sekarang bersaing bukan untuk menjual produk, tapi untuk jadi bagian dari cerita hidup manusia.
Itu sebabnya dunia pop culture terasa penuh warna, absurd, dan memikat.
Dan mungkin, untuk sesaat, di antara NFT berkilau, figur plastik mahal, dan game bergrafis gila, manusia hanya sedang mencari satu hal sederhana: rasa ingin terhubung.




